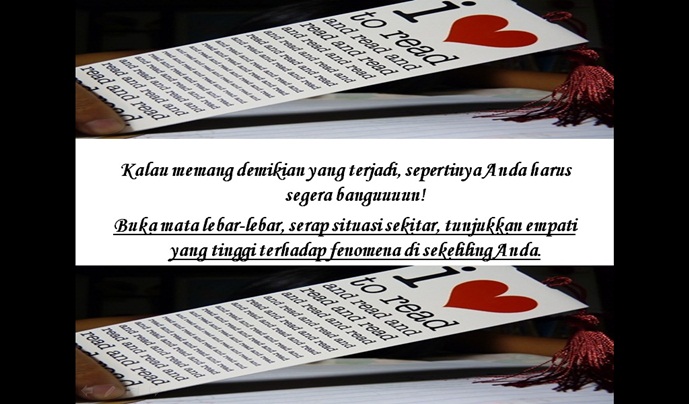Bada shalat subuh Rumondang keluar dari biliknya. Hawa dingin segera menyergap wajahnya begitu kakinya menuruni tangga kayu sopo godang1 milik kakeknya. Sebuah rumah adat Batak berbentuk panggung tinggi, terbuat dari kayu-kayu jati yang kokoh. Biliknya dari anyaman bambu dengan atap rumbia. Ketika dirinya masih kecil, di bawah panggung itulah sudut favoritnya tempat bermain rumah-rumahan bersama sepupu-sepupunya.
Di kampungnya sopo godang milik Ompung2 terbilang bangunan paling bagus. Sebab Ompung Ni Sahat adalah orang yang sangat kayaraya. Sabak3-nya tak terhitung banyaknya, lumbungnya yang selalu penuh berada di tiap sudut pekarangan dengan luas entah berapa hektar. Belum lagi hewan peliharaannya, kambing, sapi, kerbau, ayam, bebek….
Monyet-monyet bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon lainnya sambil menjerit-jerit riuh.“Iiih, bikin halak4 kaget saja!” gumamnya.
Rumondang Siregar, seorang gadis berumur 16, dengan rambut panjang lebat tersembunyi di balik jilbab kaos berwarna putih. Tubuhnya yang tinggi ramping terbalut dalam stelan baju olah raga. Dia baru usai Ebtanas SMU di Padang Sidempuan, masih harap-harap cemas nilai-nilainya akan sebagus prestasi sebelumnya. Rasa cemasnya sesungguhnya tidak perlu. Sebab siapapun sudah tahu, Rumondang hampir tiap tahun menyabet peringkat pertama di sekolahnya.
Ia tersenyum simpul sendiri. ”Kalian itu tak bisa kompak pula rupanya, ya?” katanya sambil memerhatikan makhluk-makhluk lucu yang bergelayunan tak jauh dari atas kepalanya. Dia sama sekali tidak merasa takut. Sebab sejak kecil dirinya sudah akrab dengan binatang-binatang lucu itu.
Rindu pula rupanya kalian itu sama aku, ya? Hihi, sudah lama juga tak ketemu kita nih. Salah siapa coba? Aku sibuk Ebtanas sementara kalian sibuk bergelayunan terus, ya? Rumondang terus berceletoh dalam hatinya.
Mulanya dia berjalan santai, menapaki jalan setapak menuju Utara kampungnya. Hanya saat dia melintasi sungai tiba-tiba entah mengapa bulu romanya meremang. Sepi, senyap dan memang sungguh lengang. Ke mana saja orang-orang itu? Kan biasanya juga ramai di sungai ini?
“Wuiih! Wuiih….” Tangannya sibuk menepis-nepiskan rumput ilalang yang menghalangi jalannya. Ilalang setinggi orang dewasa begitu lebat bagai tak bertepi. Namun tubuh ramping itu terus menyelusup di antara ilalang, pepohonan dan semak belukar.
“Ooh, iya, ya…. Ini musim panen raya,” gumamnya membatin.
Rumondang baru teringat kembali akan percakapannya tadi malam dengan Bou5 Taing, saudara perempuan ayahnya.
“Tiap subuh orang sini sudah berangkat ke sabak. Bagaimana dengan kau? Apa kau mau ikut kami besok itu, Butet?” tanya Bou Taing.
“Iya, bantulah kami panen, Butet!” kata Tigor, suami Taing.
“Maaf, kalau besok aku tak bisa. Aku mau ke kubur Ompungboru7,” sahutnya tegas. Tak ada yang melarang atau membantah, bahkan tak ada yang berkata-kata lagi. Memang sejak dulu pun sikap mereka selalu begitu. Tak pedulian terhadap dirinya. Biarlah, daripada mendengar omelan dan sumpah serapah Bou Taing. Sebab sekalinya bicara, omongan perempuan itu sering amat melukai hatinya.
“Anak Cina itu takkan kerasanlah lama-lama di kampung. Seharusnya kau tinggal di kotalah itu, Amoy!”
“Pergilah ke keluarga Cina kau itu di Medan!”
Baiklah, anak Cina, katanya tandas. Tanpa tedeng aling-aling. Ibu yang melahirkan dirinya memang seorang wanita keturunan Tionghoa. Wu Siao Lien nama Tionghoanya. Nama pribuminya Maharani Sanjaya. Cantik jelita wajah ibuku itu dalam potretnya, pikir Rumondang. Ya, dia hanya mengenalnya dalam potretnya. Sebab dia sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak berumur setahun. Bukan ditinggalkan ke alam baka, tapi entah pergi ke mana.
Rumondang takkan melupakan hari-harinya ketika kanak-kanak. Perilaku neneknya dan saudara-saudara ayahnya sering menyakiti perasaannya. Bahkan bukan saja secara batiniah melainkan juga fisiknya. Serasa masih terngiang-ngiang di telinganya omongan Ompungboru.
“Ibu kau itu minggat, Butet!”
“Kalau sudah besar nanti, kau pun akan benci sama ibu macam si Siao Lien itu. Percayalah sama aku!” ujarnya ketika Rumondang kelas enam SD.
“Tapi kenapa, Pung?”
“Si Siao Lien itu bukan boru8 baik-baik, mengerti?!” cetusnya bernada penuh kegeraman dan kebencian.
“Eh…. Jadi, macam perempuan mana pula Ibuku itu, Pung?”
“Pokoknya perempuan tak baiklah Ibu kau itu, Butet!” dengusnya mengulang-ulang, entah untuk ke berapa kalinya.”Dia itu tak bisa diajak hidup sengsara sama suami….”
“Artinya, dulu memang betul orang tuaku itu pernah hidup sengsara di kampung kita, ya Pung?” tukas Rumondang.
“Hanya sebentar. Tak ada kerjanya pula selain mengurung diri di kamar. Entah bikin apa itu, mengetik…?”
“Mengetik, Pung? Mengetik apa? Sebenarnya apa pekerjaan ibuku dulu, Pung?” Ini kesempatan baik untuk mengorek perihal orang tuanya. Biasanya tak ada seorang pun yang mau menyinggung perihal mereka. Terutama tentang ibu kandungnya. Seakan-akan telah menjadi tabu, pantangan berat bagi keluarga besar ayahnya.
“Kurasa dia itu cuma ikut-ikutan anakku saja,” kata perempuan tua itu sambil menumbuk padi dengan kekuatannya yang luar biasa. Sering Rumondang merasa heran akan kekuatan fisik yang dimiliki perempuan tua berperawakan tinggi besar itu. Ompungboru mengerjakan segalanya seorang diri!
“Kata Uda Tigor, ayahku itu seorang seniman, Pung?”
“Iyalah, betul itu! Sudah jadi seniman terkenal anakku itu sebelum kawin sama si Siao Lien. Orang bilang penyair, begitulah…. Gara-gara kawin sama halak Cino, kacau pulanya hidup anakku itu! Jadi Sampuraga8-lah dia itu. Bah!”
Tiba-tiba perempuan tua itu berhenti menumbuk. Sepasang matanya dilayangkan ke kejauhan, ke ufuk langit berwarna biru bening. Rumondang sering berpikir, adakah Ompungboru pernah merindukan putranya? Anak laki-lakinya semata wayang? Sebab seingatnya, neneknya tak pernah memperlihatkan kerinduannya kepada siapapun. Kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, penyokong utama keluarga besarnya sudah menguras seluruh enerjinya.
Namun, kalau untuk urusan sumpah serapah…. Dialah biangnya!
“Hei, sudahlah jangan mau tahu cerita orang tua kau. Sekarang kau ini kan sudah lama ditinggalkan sama mereka. Kau ini dibuang, Butet. Makanya kau harus bisa menitipkan diri. Jangan banyak main. Sekolah juga tak usahlah tinggi-tinggi. Diam sajalah kau di rumah. Kerja di sabak, menyangkul, panen, menggembala ternak, bantu-bantu aku…. Cukuplah begitu kehidupan kau itu, Butet!” ceracaunya tak tertahankan lagi.
Syukurlah, Sang Maha Pencipta menjemput neneknya tak lama setelah Rumondang lulus SD dan sangat menginginkan melanjutkan sekolah. Neneknya meninggal akibat dehidrasi, muntaber. Tak mau dibawa ke Puskesmas atau dokter. Bahna malas dan kikirnya mengeluarkan isi kocek yang selalu disimpannya dengan sangat telaten di lemari tuanya.
Memang ada bagusnya bagi Rumondang ditingalkan oleh Ompungboru. Karena perilaku dan keinginan sang nenek sangat berbeda dengan nenek-nenek temannya. Apabila nenek temannya punya keinginan melihat dan memajukan anak cucu, mengejar cita-cita. Seperti Ompung si Liani, meskipun sangat miskin, bersikukuh menyekolahkan anak dan cucu ke perguruan tinggi. Dibela-bela walau harus berutang sana-sini, menggadaikan bahkan sampai menjual seluruh harta benda.
“Kalau Ompungboru masih ada, tentu aku takkan bisa sekolah di Sidempuan macam sekarang, ya Pung?” cetus Rumondang ketika diantar oleh kakeknya ke tempat kos di Kabupaten. Saat itu dia akan melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMU. Di kampungnya belum ada SMP. Jadi ketika SMP pun dia harus berjalan kaki sepuluh kilometer pulang dan pergi ke kecamatan.
"Iyalah. Aku pun takkan kawin lagi sama si Joruk, bekas teman kau itu,” sahut kakeknya sambil terkekeh.
Rumondang mesem dan menggoda kakeknya.”Jadi, lebih suka mana, Pung? Saat masih ada Ompungboru atau sekarang?”
“Ah, macam mana pertanyaan kau itu? Menggoda aku saja, ya?” elaknya tersiup malu, tapi sesaat kemudian dilanjutkannya. ”Tapi Butet, kalau aku pikir-pikir pula, bah! Enakan sekaranglah kita ini, ya Butet? Tak ada lagi tukang sumpah-serapah di rumah. Artinya, dingin kuping bening matalah kita ini. Iya kan, Butet?”
Rumondang tertawa tergugu melihat kelakuan kakeknya. Belum 40 hari meninggal Ompungboru, ketika Ompung menikah lagi. Joruk, bekas sobat kecilnya, teman bermain di sungai dan mengaji di surau. Tentu saja mulanya tindakan kakeknya itu menjadi gunjingan orang sekampung. Namun, kemudian reda sendiri.
Siapa pula yang berani ganggu-gugat kakeknya? Orang yang paling berkuasa, banyak harta, baik budi, ringan hati dan selalu berbagi dengan masyarakat sekitarnya.
Seorang pelopor pendidikan di desa mereka. Karena pernah berkelana ke Malaysia, Makkah dan Irak. Biarlah Sang Khalifah punya istri lagi, pikir mereka. Lagipula, memang diwenangkan meski dia ingin punya istri sampai empat sekalipun. Iya kan? Apalagi ini sedang melajang kembali. Siapa pula yang mau kedinginan sendirian, menjelang hari-hari senja dalam hidupnya? Nah, yang penting dia tetap baik hati, selalu ikhlas berbagi hartanya dengan masyarakat.
Walau mendapat tentangan hebat juga dari anak-anak Ompungboru. Ompung tetap melanjutkan niat dan hasratnya, menikahi remaja belasan sebaya cucunya. Dia merasa sudah cukup adil, membagikan sebagian hartanya dengan anak-anaknya. Hidup akan terus berlanjut baginya. Setelah dua per tiga hidupnya dihabiskan dengan seorang istri nyinyir. Dia masih ingin menikmati sisa-sisa hidupnya dalam suasana yang sangat berbeda.
“Hmm, Ompung… Ompung,” gumam Rumondang sambil mesem-mesem sendiri. Teringat kembali bagaimana saat kakeknya begitu keras kepala, melaksanakan keinginannya menikahi Joruk. “Tak takut dimusuhi anak-anaknya, tetap berkeras menikahi Joruk. Hm, sebenarnya alasan apa, ya Ompung itu? Segitu umurnya konon sudah 105 tahun?!”
Ah, tapi meskipun sudah lebih seabad begitu, penampilan kakeknya tampak tegar. Gigi-giginya masih banyak, rapi dan kokoh. Matanya pun masih awas, tanpa kacamata. Perawakannya juga sama sekali tidak bungkuk, apalagi peot. Ompung masih gagah, kuat dan tegar sekali. Dan suaranya bila sedang mengajari anak-anak mengaji atau markobar9 itu; subhanallah, begitu lantang dan bening!
“He, tunggu!”
Di atas sebuah rambin10 bambu. Ada seseorang yang menyapanya lantang. Rumondang merandek dan kehilangan seluruh lamunannya. Di depannya menjulang seorang wanita separuh baya. Dia meletakkan bawaannya berupa sekarung padi, yang semula dijunjung di atas kepalanya. Agaknya hendak dibawa ke poken11. Hari Kemis memang hari pasar di kampung mereka.
“Ya?” Rumondang menatapnya. Peluh bercucuran di sekujur tubuh wanita perkasa itu. Wajahnya yang persegi, wajah khas wanita Batak tampak memerah dan kehitaman. Seraut wajah yang akrab dengan sengatan matahari.
“Cucunya si Ompung Ni Sahat kau ini, ya?” cetusnya sambil tersengal-sengal, berusaha meredakan napasnya.
“Eee, iya…. Siapa, ya?” Rumondang balik bertanya. Dia sungguh mengagumi kekuatan dan kemandirian wanita-wanita perkasa di kampungnya. Termasuk wanita di hadapannya juga mendiang neneknya.
“Alaaah kau ini….” Ditepuknya pipi Rumondang agak keras, hingga gadis itu terkejut. ”Sombong ‘kali, bah! Aku ini Inangboru kaulah itu, Butet! Si Sagala, ingat kau sama anak sulungku itu kan?”
“Bang Sagala yang di kampung seberang. itu, ya?”
“Iyalah itu! Masa pula kau lupa sama anakku itu? Calon suami kaulah dia itu, Butet…. Kapan kau datang dari Sidempuan?”
“Eeeh, eeh, tadi malam…” sahut Rumondang dengan wajah bagai terbakar. Orang tua ini kok tanpa tedeng aling-aling ‘kali, bah! Pake mengaku-aku anaknya calon suamiku segala? Rumondang mendumel dalam hati.
“Sudah lulus kau sekarang, ya Butet?”
“Sudah, eeh, maksudku lagi tunggu pengumumanlah…”
“Kalau kau ini pastilah lulus. Pintar kan kau ini, Butet. Macam Ibu kau itu, cantik dan pintar…. He, mau ke mana memangnya kau ini?”
“Ke kubur Ompung, Bou.”
“Jangan lupa nanti mampir ke rumah kami, ya. Abang kau si Sagala lagi di rumah. Menganggur dulu dia sekarang, motor ojeknya lagi ngadat….” Berkata begitu tangan-tangannya yang kokoh mengangkat kembali karung bawaannya. Pleeek, ditempelkan kembali di punggungnya. Tanpa minta bantuan siapapun. Selang sesaat perempuan itu sudah berjalan cepat melintasi sisa rambin menuju poken.
Rumondang geleng kepala. Kekuatan perempuan itu mengingatkannya kepada mendiang neneknya. Kuat bagai banteng ketaton neneknya itu. Kalau musim panen neneknya akan turun langsung sendiri. Sering mengangkuti padi berkarung-karung dari pesawahan ke rumah mereka. Perjalanan jauh lima-enam kilometer, terus diangkuti bolak-balik dan berhari-hari demikian. Sejak muda hingga tua. Aneh, padahal neneknya seorang istri orang berada.
“Menyuruh halak kau bilang, Butet? Bah! Baiknya aku kerjakan saja sendiri. Biar hematlah kita!” begitu dalihnya selalu setiap kali Rumondang mengasihaninya.
Menurut cerita Ompung, saat pertama kali mereka menikah pernah neneknya diajari membaca dan menulis. Sekali-dua masih mau mematuhi suami. Namun, hari-hari selanjutnya neneknya lebih suka memilih mengambil cangkul dan pergi ke sawah. Mendingan mencangkul tanah keras bagai cadas daripada belajar baca tulis, katanya. Karena itu sampai akhir hayatnya neneknya tetap seorang buta huruf.
Namun, anehnya dalam hal hitung menghitung penjualan hasil panen…. Tak perlu kalkulator lagi!
Orang sekampung sudah mengetahui hal itu. Kakek gemar membaca, mencari ilmu dunia-akhirat seakan tak pernah henti. Sebaliknya neneknya mengelola harta peninggalan leluhur dengan telaten dan cermat.
Sering pula neneknya mengeluh. ”Mau tahu kerja Ompung kau itu, Butet? Begitu sajalah dari dulu, baca buku, kitab, mengaji. Kalau bosan pergi dia ke lapo tuak12 sama teman-temannya!”
@@@
1rumah adat Batak
2kakek atau nenek
3sawah
4orang
5sebutan untuk tante, adik perempuan bapak
7nenek perempuan
8 perempuan
8 nama tokoh legenda Batak kisahnya mirip Malin Kundang
9 berbicara dalam suatu pertemuan adat keluarga
10 jembatan
11 pekan, pasar kaget seminggu sekali
12 kedai tuak

.jpg)